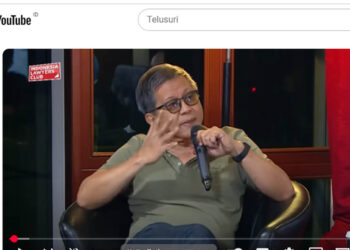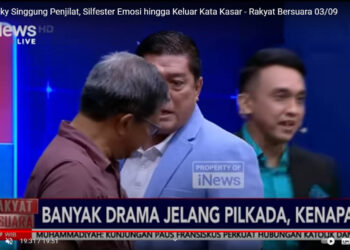Ramai soal sosok Rocky Gerung belakangan, seolah dirinya diposisikan seperti selebritas yang bercerai lalu kawin lagi.
Membicarakan dirinya kebanyakan hanya berkutat pada soal suka atau tidak suka, simpatisan atau oposan, bahkan mungkin moral dan amoral.
Bagi para pendukungnya atau minimal penyukanya, setiap kritikan mbalelo Gerung seolah menambah kekuatan politik untuk ‘melawan’ hegemoni kekuasaan, di sisi lain, pernyataan-pernyataan Gerung yang menggelitik, kerap mengganggu bahkan tak lebih dari sekadar ‘sampah akademis’ yang memenuhi lini media massa.
Gerungisme menjadi ‘oase’ di tengah fanatisme politik yang saling berhadapan, terlepas dari ide, gagasan, bahkan narasi-narasinya yang terkesan kontradiktif.
Hampir seluruh narasi Gerung yang diungkapkan—dan yang paling banyak di media sosial—lebih cenderung bernarasi ‘penghinaan’—jika tak boleh disebut kritis.
Diksi ‘bodoh’, ‘dungu’, atau ‘akal sehat’ barangkali menjadi ikon naratif pendiri Setara Institute ini yang belakangan malah dilaporkan oleh pihak-pihak yang terganggu dengan berbagai ceramahnya.
Sosok Gerung yang terus menuai kontroversi seolah terus dipersekusi agar siap menghadapi konsekuensi hukum atas segala hal yang diperbuatnya dan ia dibidik karena ucapannya soal ‘kitab suci fiksi’, suatu diksi hukum terkait ujaran kebencian yang sarat nuansa politik dibelakangnya. Pernyataan yang sudah kadaluarsa ini seolah menegaskan bahwa ‘gerungisme’ harus diberantas hingga akar-akarnya karena mengganggu dalam konteks politik dan bahkan agama.
Saya tak mengenal Gerung dan mungkin juga Anda yang banyak menulis soal Gerung lalu dibagikan dalam berbagai ranah media sosial.
Kritik pada sosok Gerung lalu dikait-kaitkan dengan latar belakang dirinya sebagai akademisi yang bergelut dalam dunia ilmu filsafat.
Hampir semua narasi yang menyoal Gerung adalah menyerang—untuk tidak menyebut melakukan kritik—yang tampak canggung membedah setiap narasi Gerung dari sisi ilmu filsafat.
Padahal, filsafat tentu saja ilmu kritis bahkan sangat radikal dalam membahasakan apapun sehingga hampir tak ada kebangunan suatu kenyataan ilmiah yang lepas sama sekali dari filsafat di dalamnya.
Berfilsafat berarti ‘bebas nilai’ dalam hal berpikir dan membangun argumentasi secara logis dan terbuka dalam hal kritik asal dibangun secara logis pula dan bebas dari nilai-nilai moralitas agama.
Anehnya, banyak kalangan anak muda muslim progresif yang menyampaikan kritik atas Gerung, tetapi hanya berkutat pada soal diksinya menyoal diksinya tentang ‘politik akal sehat’, yang dibenturkan secara nyata pada konteks besar kecenderungan pilihan politik.
Padahal, Gerung yang memang seorang partisan politik tidak dalam konteks menyetubuhi kelebihan berpikir filosofisnya dengan tujuan melahirkan ‘anak-anak’ filsafat yang partisan.
Banyak orang yang terganggu dengan pernyataan Gerung karena dianggap menyerang penguasa, padahal dalam suatu iklim demokrasi mengkritisi dengan warna apapun tentu saja bentuk kewajaran yang tak perlu dipersoalkan.
Sangat
berlebihan ketika kemudian, soal “dungu” yang populer dinarasikan Gerung lalu
dikaitkan dengan kajian kitab-kitab klasik kalangan pesantren yang tiba-tiba
mempersalahkan setiap narasinya.
Padahal, soal kajian filsafat dalam tradisi
keilmuan Islam sudah diperdebatkan sejak abad 11, ketika Imam Al-Ghazali
membuat suatu karya monumental ‘Tahafut Al-Falasifah’
yang menyerang bahkan ‘mengkafirkan’ para filosof yang mengedepankan cara
berpikir bebas nilai soal kenyataan penciptaan Tuhan atas alam semesta.
Sekalipun Al-Ghazali mengkritik begitu keras para filsuf muslim, tetapi tak sampai mengganggu wacana pemikiran Islam yang terus berkembang—tanpa pretensi politik apapun—dari zaman ke zaman.
Memang sudah lumrah, bahwa dalam membaca dan memahami suatu ide atau gagasan, terlebih tertuang dalam bentuk teks, kita tidak bebas dari prasangka. Nothing is understood that is not construed, begitu kata Schleiermarcher.
Tidak ada pemahaman tanpa melibatkan suatu penafsiran dan kebanyakan tentu saja bias dan cenderung bermakna subjektif.
Lalu, bagaimana seharusnya dalam alam filsafat dapat lebih objektif dalam menilai suatu kebenaran?
Jika soal pernyataan seseorang itu memiliki korelasi positif antara pernyataan dan kenyataan, maka terori korespondensi menilainya sebagai suatu kebenaran.
Maka, seharusnya ketika alam filsafat banyak dibahas dalam mengoreksi kehadiran “Gerungisasi”, diperlukan sikap saling mendengarkan (reciprocal listening), toleransi, dan saling menghargai (mutual respect).
Namun, sulitnya kenyataan yang dipengaruhi beragam aktivitas politik sekaligus mendapat tambahan dari beragam informasi yang sudah ‘dipelintir’ dan ‘dipolitisir’, banyak narasi-narasi ilmiah yang kemudian tunduk pada kenyataan politik bukan sebaliknya.
Mereka-mereka yang terlampau disibukkan oleh suasana membangun klarifikasi dan saling beradu pendapat, tak ubahnya kelompok pemandu sorak yang jingkrak-jingkrak jika kubu politiknya menguasai panggung kekuasaan.
Politik tak ubah seperti medan hasrat pemuasan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap persepsi besar siapa lawan dan mana kawan dan yang paling menggelikan mereka sibuk menafsirkan beragam pesan simbolik seseorang seraya menjauhi secara substantif nilai-nilai kepolitikan itu sendiri.
Menilai keberadaan Gerungisme saya kira tak lebih dari upaya suatu pembangunan opini dengan diksi yang kritis terhadap kekuatan ‘maha besar’ penguasa.
Menempatkan Gerung sebagai akademisi yang ‘menyesatkan’ lewat pembangunan narasi filosofisnya yang memang menohok kekuasaan tanpa melepaskan diri dari cara pandang kepolitikan, justru terkesan tampak naif.
Bagi saya, tahun politik jelas berdampak pada relasi kritis para oposan dalam berbagai bentuknya kerap kali disandera bahkan dijegal melalui upaya-upaya kekuatan politik tertentu—untuk tidak menyebut adanya praktik kriminalisasi.Jika Gerung lantang menarasikan argumentasinya yang bertentangan dengan mainstream dan memposisikan dirinya sebagai pihak oposan, lalu dihalang-halangi atau dipersekusi secara akademik maupun politik, jelas ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Politik akal sehat Gerung yang bernada kritis bahkan tampak provokatif, memang seringkali dipandang berbahaya oleh pihak penguasa atau mereka yang memiliki kecenderungan politik pro penguasa.
Sekalipun dalam konteks politik, penggunaan akal sehat tentu saja tidak tepat, karena politik sesungguhnya adalah kepentingan yang seringkali tak dipandu akal sehat.
Gerungisme tentu saja diposisikan sebagai ‘anti-mainstream’ bahkan dianggap melawan arus besar kekuatan politik tertentu.
Sehingga wajar jika ada sebagian anggapan bahwa apa yang disampaikannya hanya sampah, tak bermanfaat dan harus dibuang jauh-jauh agar tak lagi ‘dipungut’ oleh masyarakat pengaisnya.
Saya bukan pengagum Gerung dan tidak berada dalam barisan Gerungisme yang belakangan fenomenal secara politik.
Bukan hak saya menilai Gerung seperti apa dan berpihak ke mana, karena sejauh ini yang muncul di ranah publik tak lebih dari sekadar asumsi-asumsi politik yang ‘berkecenderungan’ bukan penilaian atas realitas akademis yang berasal dari belakang batok kepala mereka.
Mungkin kalangan golput tak peduli dengan kenyataan politik yang cenderung partisan atau jatuh dalam kubangan ‘fanatisan’.
Pasalnya, siapapun berhak atas kebebasannya berpikir, bertindak, berprilaku dan masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, murni tanpa pretensi kepolitikan apapun di belakangnya.
Penulis: Syahirul Alim