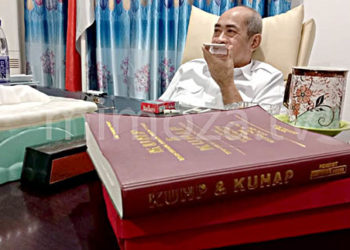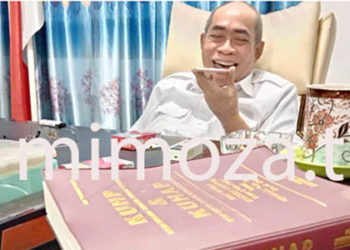Oleh: Funco Tanipu
Risma menjadi trending topik nasional. Kejadiannya saat Risma memarahi Pendamping PKH di Gorontalo beberapa hari lalu. Kejadian tersebut direkam seseorang dan kemudian disebarkan melalui WhatsApp. Setelah itu, lahir berbagai pendapat dan polemik.
Saya fokus pada “marahnya” Risma dan bagaimana orang Gorontalo memandang perilaku marah dalam perspektif antropologi.
Kemarahan Risma menurut saya bukan sesuatu yang spontan. Kemarahannya adalah rangkaian peristiwa dan kejadian serta latar belakang kultural Risma itu sendiri.
Dalam perspektif antropologi Gorontalo, marahnya Risma bertingkat-tingkat. Risma adalah seseorang yamg “moyingowa” atau pemarah jika melihat ketidakbenaran atau kebatilan. Risma juga “mopatuwa” artinya perangainya mudah panas atau mudah marah, apalagi melihat banyak ketidakberesan aparat dalam pelayanan publik. Banyak rekaman kejadian yang bisa kita tonton soal perangai Risma, baik mulai dari Walikota Surabaya maupun saat dia menjabat Mentri Sosial.
Dua “dasar” ini adalah “kaki” perangai Risma dalam pemerintahan. Dalam konteks antropologi Gorontalo, karena banyak perulangan kejadian yang tidak beres atas tata kelola pemerintahan, maka membuat inilah yang membentuk dan menjadi “tahu-tahu atau sudah tersimpan dalam memori dan nurani.
Di Gorontalo, jika marah sudah dalam tingkat “tahu-tahu” maka dengan trigger apapun, khususnya melihat ketidakberesan yang berulang, akan segera “naik” dan pada ujungnya pendamping PKH “tilu-tilunggoiyo” alias ditunjuk-tunjuk. Molu-molunggo’o adalah ekspresi marah dalam kaidah Gorontalo. Ekspresi dari pendamping adalah “le hulo’o” atau terduduk.
Jadi, apa yang Risma ekspresikan sebenarnya ada dalam kultur keseharian orang Gorontalo. Bahkan dalam kemarahan orang Gorontalo yang lain, jima sudah “tahu-tahu” marah, maka ada beberapa yang akan “anu-anungo” atau menyelipkan pisau atau parang di balik baju untuk membalas atau mengekspresikan kemarahannya.
Kemarahan Risma menurut saya masuk juga dalam varian marahnya orang Gorontalo yakni “lombu-lombula nyawa” artinya itu berarti kiasan seperti merebus air yang mendidih. Dalam arti lain, marahnya Risma sudah berada “mato yimbupulu” atau sudah berada di ubun-ubun.
Marah dalam perspektif orang Gorontalo sangat beragam. Mulai dari yingo, moyingowa, yingo ma’o-yingo ma’o, yiyingowa, mayile yingo dan banyak ragam ekspresi lainnya.
Ada yang ekspresi lanjutan dengan sabar dan menyerahkan ke Allah dengan “mapilooyonga liyo” dan ada yang “maletahu yingo” artinya marahnya disimpan, sewaktu-waktu bisa meledak. Risma masuk kategori kedua, maletahu yingo.
Pertanyaannya, apakah marah adalah keburukan atau tidak? Dalam konteks antropologi Gorontalo, marah dengan segala variannya adalah bagian dari kearifan lokal. Kenapa bisa disebut arif? Karena marah adalah untuk meluruskan yang tidak beres. Ada ketidakbecusan dalam mengelola sesuatu.
Di konteks Gorontalo, seorang pemimpin atau disebut “wuleya lo lipu” harus punya sifat marah. Karena sesuai janji adatnya, “huta, huta lo ito Eeya” (tanah, tanah milik Allah), “taluhu, taluhu lo ito Eeya” (air, air milik Allah), “dupoto, dupoto lo ito Eeya” (angin, angin milik Allah), “tulu-tulu lo ito Eeya” (api, api milik Allah).
Dalam konteks itu, seorang pemimpin sebagai “wakil” wajib menjaga alam dan segala apa yang ada kaitannya dengan sepenuh hati. Marah adalah salah satu sifat untuk menegakkan kebenaran. Itu termaktub dalam kalimat adati hulo-hulo’a to Syara’a, Syara’a hulo-hulo’a to Quruani (adat bersendikan syara’, syara bersendikan Qur’an). Artinya, ada ruang dan kewajiban menegakkan amal ma’ruf dan nahi munkar.
Pertanyaan kemudian, apakah perilaku marahnya Risma itu bisa menyelesaikan sesuatu atau membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik? Risma telah mencontohkan kebiasaan marahnya telah membuat Surabaya meraih 322 penghargaan baik nasional maupun internasional. Di level internasional, Risma mendapatkan penghargaan sebagai Walikota Terbaik Dunia dari citymayors.com. Risma juga dianugerahi walikota ketiga terbaik dunia dari World Mayor Project hingga ia menjadi tokoh urutan ke 24 dari 50 tokoh dunia versi Fortune.
Di wilayah Asean, Risma pernah menjadi Ketua Asean Mayors Forum, yang saya menjadi saksi bagaimana Risma bisa menjadi pusat perhatian saat Asean Mayors Forum di Bangkok tahun 2019 silam.
Maksud saya menulis ini untuk menjernihkan persoalan, bahwa marahnya Risma tidak bisa dilihat dari satu perspektif, tapi multi perspektif.
Memang banyak yang menginginkan harusnya Risma sebagai pemimpin ada sifat “toliango” atau kasih sayang. Tapi, makna toliango tidak bisa ditafsirkan satu jenis saja yakni sayang saja, marah pun adalah bagian dari toliango.
Coba kita perhatikan orang-orang tua kita, sering marah pada kita. Itu bukan “yingo” tapi “toliango”. Jadi “toliango” harus didudukkan secara lebih proporsional.
Jadi, yingo dan toliango dalam konteks Gorontalo adalah sesuatu yang melekat dan terpadu satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan. Karena bisa saja, misalnya jika kita lihat pada kakek dan nenek kita yang begitu sayang pada cucunya dengan cara “hepopohidiyo liyo” maka banyak contoh jika anak tersebut kelak akan jadi “jamodungohe” dan bahkan “kapala angi” dalam konteks negatif. Karena kasih sayang yang berlebihan.
Sebagai penutup, saya mengajak agar kita lebih proporsional dalam melihat peristiwa yang terjadi. Problem inti sebenarnya bukan soal marah, tapi soal ketidakberesan manajemen data yang memang amburadul. Tapi jika dalam beberapa waktu kedepan misalnya hal ini tetap tidak beres dan tidak ada perubahan, maka Risma bisa saja kita sematkan “yingo ma’o-yingo ma’o” atau “moyingo jato tambati liyo”. Sebab, dia juga bertanggung jawab sepenuhnya atas manajemen data yang buruk, walaupun ia mewarisi hal yang buruk itu saat ia baru beberapa bulan masuk ke lingkungan kementrian yang ia pimpin, maka dia harus menunjukkan efekifitas marah yang ia terapkan saat di Surabaya lalu.